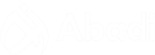Perseteruan politik yang terjadi pada tahun 1950-an, bukan hanya soal pertarungan ideologis--yang melibatkan kubu Islamis, nasionalis, dan komunis--namun juga meruncingnya perbedaan pendapat antara Islam tradisionalis dan Islam modernis di tubuh Masyumi.
Puncaknya, tahun 1952, NU menyatakan diri keluar dari Masyumi. Rais Am NU kala itu, KH Wahab Chasbullah yang mempelopori keputusan tersebut. Kiai Wahab dan tokoh-tokoh lainnya tidak puas dengan hasil voting yang memenangkan K.H. Faqih Usman sebagai kandidat menteri agama dari Masyumi. Mulanya NU menawarkan K.H. Wahid Hasyim dan empat kandidat lainnya sebagai cadangan. Namun dalam rapat, K.H. Masykur yang maju mewakili NU. Tapi kalah voting.
Minimnya tokoh-tokoh NU dalam jajaran eksekutif, membuat NU merasa dikucilkan dari Masyumi. Merasa tidak didengar. Merasa tersingkir dari peran-peran strategis dalam partai. Meski jabatan ketua majelis syuro Masyumi saat itu masih dipegang KH. Hasyim Asy'ari, NU menilai itu tidak terlalu menguntungkan. Mengingat fungsi majelis syuro dalam AD/ART partai terbaru hanya memberikan pertimbangan kepada pemimpin partai jika diminta. Putusan tersebut adalah hasil Kongres 1949 yang menganulir kewenangan majelis syuro pada periode sebelumnya.
Perbedaan pandangan antara M. Natsir sebagai pemimpin Masyumi dengan KH Wahab Chasbullah sebagai pemimpin NU yang kerap kali terjadi menambah tidak harmonisnya kedua kubu itu. NU lebih dekat pada pemikiran-pemikiran Sukiman Wirdjosandjojo ketimbang M. Natsir.
Greg Fealy, penulis buku "Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967" menyebut penarikan diri NU dari Masyumi sebagai guncangan terbesar dalam sejarah perjalanan politik Islam di Indonesia. Akibatnya, pada Pemilu 1955, Masyumi gagal meraih suara terbanyak dan harus puas di urutan kedua setelah PNI. Padahal andai NU masih menjadi bagian dari Masyumi, tentu akan lain cerita. Jika suara NU dan Masyumi digabung, maka akan jauh melampaui suara dan kursi PNI di parlemen.
Tapi dinamika politik itu memberikan pelajaran yang berarti. Perbedaan pendapat adalah hal niscaya, hatta di dalam tubuh partai politik Islam sekalipun. Ia bisa memperkaya ide-ide dan pemikiran, tapi juga tak jarang berujung pada perpecahan. Kebesaran jiwa dalam menerima setiap keputusan musyawarah adalah kuncinya. Semua pertarungan pendapat bisa mengemuka, namun harus tunduk dan tiarap saat keputusan musyawarah sudah diambil melalui mekanisme yang benar dan semestinya.
Pada Muktamar NU ke-19 di Palembang, 28 April-1 Mei 1952, secara resmi NU memutuskan diri keluar dari Masyumi. Keputusan ini bukan berarti NU memecah persatuan umat Islam. NU menolak jika dikatakan demikian. Karena itu, untuk menepis tuduhan tak sedap tersebut, bersama PSII dan Perti, NU mendirikan Liga Muslimin Indonesia.
KH Syaifuddin Zuhri mengatakan bahwa keputusan NU memisahkan diri dari Masyumi adalah pilihan terakhir yang tak dapat dielakkan. Ketidakcocokan terhadap struktur partai dan strategi-strategi perjuangan disebut-sebut sebagai faktor penyebab terbesar. Menurutnya, langkah-langkah Masyumi bisa merugikan umat Islam.
Lain lagi dengan jawaban M.Natsir, ketika ditanya oleh wartawan Editor. Perihal sebab kenapa NU keluar dari Masyumi. "Begini," kata beliau. "Waktu ada musuh di depan kita, mudah sekali mempersatukan tenaga. Semuanya serba 'kita' : ini perjuangan kita, ini pengorbanan dan keberhasilan kita. Tapi kalau musuh itu tidak tampak lagi, maka perkataan 'kita' ditukar dengan 'kami'. Tegasnya, mana bagian saya dan mana bagian kamu. Itulah kemudian yang terjadi."
"NU dan Masyumi," lanjut M.Natsir, "sama saja penyakitnya, yaitu menghitung-hitung antara 'kami' dan 'kamu' itu."
Sampai sekarang pun, cita-cita untuk mempersatukan umat Islam dalam satu wadah perjuangan politik masih jauh panggang dari api. Partai-partai Islam baru justru bermunculan. Mereka enggan bergabung dengan partai-partai yang sudah ada. Apa sebabnya?
Mungkin benar kata M.Natsir, karena faktor "kamu" dan "kami" itu. Tapi Kiai Saifuddin Zuhri mungkin juga benar: semua sama dalam tujuan, hanya saja memilih bersimpang jalan, karena perbedaan pendapat dan keyakinan.
Politik bukan tujuan. Politik hanya alat, hanya cara, hanya sarana. Tujuannya sama: masyarakat yang sejahtera.
*Pimred abadi.web.id
Cancel